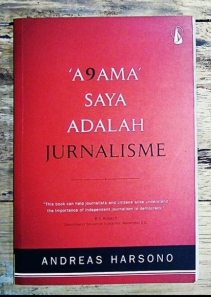
Buku ini sudah lama jadi bucketlist karena ke-kepoan saya pada kitab sucinya para jurnalis. Waktu pertengahan tahun lalu, buku ini sudah sempat saya beli secara online namun tidak jadi dikirimkan ke alamat saya, alih-alih malah saya jadikan kado sebagai tanda perkenalan juga sekaligus hadiah ulang tahun kawan baru saya, seorang jurnalis muda. (Mungkin sampai saat ini orangnya juga tidak sadar karena lalu saya kirim tanpa nama beserta Baju Bulan Joko Pinurbo sebagai sisipan tambahan eh atau SGA ketika jurnalisme dibungkam, saya pun lupa). Lalu, saya menunda kembali memilikinya walau sesekali ketika berkunjung ke tempat teman (yang juga jurnalis), saya curi-curi baca laman per lamannya. Hingga akhir bulan kemarin, buku ini ada di genggaman saya. And finally, “A9ama saya adalah jurnalisme” berhasil saya lahap ditengah-tengah jadi supirnya saya di hari kompensasi untuk keluarga yang sering banget ditinggal kerja demi sesuap nasi dan spp pascasarjana yang entah kapan selesainya ini, sehingga butuh belasan hari baru terselesaikan dengan baik.
Eh intronya kepanjangan ya?
Oke, saya akan mulai review buku dengan tebal 286 halaman ini yang sudah terbit 7 tahun silam (Iya, tau. Saya cukup ketinggalan zaman untuk membacanya, tapi lebih baik terlambat daripada tidak tahu sama sekali toh?). Buku ini ditulis oleh Andreas Harsono, bagi yang belum tahu, beliau adalah seorang jurnalis senior yang telah mengecap pengalaman bekerja di berbagai media, baik dalam negeri maupun internasional. Beliau juga seorang peneliti untuk Human Rights Watch dan pernah menerima beasiswa jurnalistik idaman ‘Nieman Fellowship’ dari Universitas Harvard. Pada kesempatan itu Beliau mengenal Bill Kovach -salah satu penulis kitab The Elements of Journalism. Pertemuannya tersebut sepertinya berperan besar dalam kelanjutan kariernya sebagai jurnalis. Pada buku ini terlihat seberapa besar rasa hormat dan kekagumannya kepada Bill Kovach yang reputasinya sulit diragukan oleh siapa pun. Dalam memandang persoalan-persoalan pada buku ini, sosok jurnalis tersohor itu sering kali menjadi referensi utama beliau.
A9ama saya adalah jurnalisme merupakan antologi dari tulisan-tulisan di Blog beliau (bagi yang belum tahu http://www.andreasharsono.net adalah laman jejaring beliau). Buku ini dibagi menjadi empat bagian: (1) Laku wartawan, (2) Penulisan, (3) Dinamika Ruang Redaksi dan (4) Peliputan. Pembagian ini, menurut komentar dari Syarifudin, memang lazim dipakai dalam pendidikan jurnalisme. Saya tak begitu paham, karena saya tak pernah terjun langsung ke dalam dunia ini. Yang saya tangkap, buku ini mengulas dan mengkritik masalah-masalah seputar jurnalisme per kasus, diantaranya beliau mengkritisi terminologi jurnalisme islami, penggunaan byline dan firewall yang banyak absen di media lokal, perihal penyebutan referensi kedua, dan tren jurnalis melibatkan diri sebagai aktor percaturan politik. Sementara membacanya, karena belum paham betul beberapa istilah, sembarilah saya membuka Google saat membaca, mencari istilah kosakata yang menurut saya baru, namun juga tak terlalu sering sebab beberapa beliau menerjemahkan dari kata-kata tersebut dalam bukunya itu.
Dalam benak saya yang tidak begitu familiar dengan jurnalisme karena tidak pernah terjun langsung di dalamnya (walau disekitar saya dikelilingi oleh kawan yang berprofesi ini, dan bahkan pernah sempat punya mantan pacar yang entah kenapa kami putus padahal dulu pengen banget punya pasangan hidup berprofesi sebagai jurnalis), seorang wartawan haruslah independen. Maksudnya? Ya independen, ya netral. Andreas justru memaparkan, netral bukanlah prinsip jurnalisme, melainkan semangat bersikap dan berpikir independen dari obyek yang diliput. Jika wartawan ingin beropini, bisa saja, itu gunanya kolom opini. Namun perlu diingat, wartawan harus tetap melakukan verifikasi, mengabdi pada kepentingan masyarakat, dan memenuhi berbagai ketentuan lain yang termasuk sembilan elemen jurnalisme yang harus ditaati seorang wartawan.
“Wartawan yang menulis kolom memang punya sudut pandangnya sendiri …. Tapi mereka tetap harus menghargai fakta di atas segalanya,” kata Anthony Lewis, kolumnis The New York Times.
Wartawan yang menulis opini tetap tak diharapkan menulis tentang sesuatu dan ikut jadi pemain. Ini membuat si wartawan lebih sulit untuk melihat dengan perspektif yang berbeda, mendapatkan kepercayaan dari pihak lain serta menyakinkan masyarakat bahwa si wartawan meletakkan kepentingan mereka lebih dulu ketimbang kepentingan kelompok di mana si wartawan ikut bermain. Sehingga dari situlah yang membedakan antara wartawan dengan juru penerangan atau propaganda.
Kebebasan berpendapat ada pada setiap orang. Tiap orang boleh bicara apa saja walau isinya propaganda atau menyebarkan kebencian. Tapi jurnalisme dan komunikasi bukan hal yang sama.
Sehingga, menurut saya untuk menjadi seorang wartawan, tidaklah semudah mengikuti kontes idola-idolaan (walau bagi saya mungkin ini sulit juga, atau anggaplah kontes menggambar, yang sering kali saya mendapat juara selagi di bangku sekolah dahulu). Menjadi seorang jurnalis yang baik butuh waktu dan pembelajaran terus-menerus, keberlanjutan dari pemahaman tentang segala. Kalau boleh saya simpulkan dari buku ini, seorang jurnalis itu harus pintar, logis, berwawasan luas, kritis dan harus banyak membaca. Intinya, menjadi jurnalis yang baik itu bukan perkara mudah, sepertinya.
“Makin bermutu jurnalisme di dalam masyarakat, maka makin bermutu pula informasi yang didapat masyarakat bersangkutan. Terusannya, makin bermutu pula keputusan yang akan dibuat.” Bill Kovach (hal. 10)
Salah satu yang menarik yang dibahas yakni mengenai rendahnya mutu pendidikan jurnalisme di Indonesia. Contoh yang ia ambil langsung adalah almamater universitas sebelah, yang dinilai punya ‘cacat’ di ketersediaan tenaga pengajar. Dari 16 dosen tetap di Jurusan Komunikasi, hanya 3 yang punya latar belakang di bidang jurnalisme. Merujuk kepada Bill Kovach diatas, semakin baik jurnalisme, maka semakin baik pula kehidupan masyarakatnya. Untuk mendapatkan jurnalisme yang bermutu tentu saja dari jurnalis-jurnalis yang bermutu. Memang dari mana lagi? Menurut saya ini yang menjadi catatan terpenting dalam buku ini adalah bagaimana mengelola pendidikan jurnalisme di Indonesia menjadi lebih baik lagi sebab pendidikan jurnalisme adalah salah satu kunci meningkatkan mutu jurnalisme di Indonesia. Terlihat saat ini sepertinya mutu jurnalis sudah makin meningkat ketimbang kondisi 7 tahun silam saat beliau menuliskan buku ini. Lihat saja, berita yang ada kini banyak yang hilir mudik kita lihat sangat informatif bahkan edukatif. Media independen bermunculan dimana-mana, walau masih juga terlihat media bayaran, yang acapkali memberikan suguhan informasi yang bias. Namun pembaca saat ini sudah dapat jeli memilah mana media yang dipenuhi jurnalis bayaran, mana yang independen. Namun walau terbilang sebagian besar saat ini mutu jurnalis sudah makin meningkat, tetaplah seorang jurnalis harus memiliki sembilan elemen jurnalisme, yang dicetuskan oleh Kovach beserta rekannya Tom Rosenstiel, dalam buku mereka berjudul The Elements of Journalism: What Newspeople Should Know and the Public Should Expect, yang beberapa elemen tadi telah disebutkan diatas, perlu dipelajari dan dipahami serta diimplementasikan oleh jurnalis mana saja untuk mendekati menjadi seorang jurnalis bermutu tinggi.
Pada bab Dinamika Ruang Redaksi, Beliau juga tak enggan melayangkan kritiknya pada sejumlah kasus jurnalisme yang melibatkan media ternama. Diantaranya, seperti isu Tempo Vs Tommy Winata (2003) yang berujung pada diskursus penggunaan sumber anonim. Beliau menyatakan jurnalis bukan hanya bicara soal misi yang baik, tapi juga soal prosedur yang baik. Praktik pemakaian sumber anonim adalah krusial, karena tak memberi kesempatan kepada audiens untuk menentukan seberapa besar derajat kepercayaan mereka pada sumber bersangkutan. Selain itu, menarik menurut saya karena juga dibahas kasus liputan Gerakan Atjeh Merdeka serta peliputan di daerah konflik lain seperti Papua, dan Pontianak. Indonesia ternyata menyimpan begitu banyak luka, dan media turut berdosa karena menyembunyikan bahkan menyimpangkan fakta-fakta tersebut. Liputan ini menimbulkan konflik bias kebangsaan atas nama busuk nasionalisme di kalangan wartawan.
Hubungan dari analogi yang beliau paparkan dengan judul yang beliau angkat, saya menangkap kesan seolah judul tersebut dikonotasikan pada sebuah keniscayaan akan suatu kepercayaan. Menurut beliau dalam obrolan santainya di Atmajaya, Agama itu bisa juga diartikan dalam bahasa Jawa Ageman (dari bahasa Sanskerta) yang berarti “baju kebesaran”. Dalam bahasa Inggris, baju terbaik disebut “Sunday best” atau pakaian untuk pergi ke gereja pada hari Minggu. Pakaian untuk pergi menjalankan ritual ini belakangan dipakai untuk menyebut doktrin yang jadi dasar keperluan berpakaian terbaik tersebut. Di India, “agama” berarti filsafat Hindustan atau doktrin Hinduisme. Terminologi ini dipakai dalam Bahasa Indonesia sebagai “keimanan.” Namun menurut Elga Ayudi yang ikut dalam obron tersebut, dalam hal ini beliau tidak bicara tentang iman, tetapi pakaian, pakaian kebesaran. “Nah, baju kebesaran saya adalah jurnalisme.” Ada kebanggaan yang dalam kalimat tersebut terhadap cita-cita dasar jurnalisme dalam pernyataan tersebut yang kemudian ia tuliskan dalam buku tersebut.
Masih banyak lagi yang dibahas sehingga kita yang tidak banyak tahu mengenai jurnalisme, menjadi sedikit lebih tahu bahwa yang berada dalam berita itu boleh jadi bukanlah suatu kebenaran hakiki, malah (mungkin) hanya ‘opera sabun’ yang masuk dalam berita. Buku ini terbilang layak bagi yang ingin memperkaya pemahaman pemula ataupun awam mengenai konteks jurnalisme di Indonesia.
Selamat membaca untuk yang ingin membacanya! Kalo saya mah kembali menyelesaikan apa yang belum selesai aja dulu [baca: Proposal Thesis].